
oleh: Denis L. Toruan
I. Bangkitnya China dan Rezim Internasional
Pada era Perang Dingin, rivalitas antara blok barat dan blok timur dalam berbagai bidang begitu kuat. Contohnya saat AS bersama sekutu-sekutunya berusaha memblokade dunia dari “bahaya komunis” yang saat itu dipimpin Uni Soviet. Dalam tingkat internasional, ini terlihat dari berbagai doktrin AS seperti Marshall Plan (1947), maupun rezim internasional seperti Bretton Woods (1944) yang kemudian melahirkan International Monetary Fund (1945) dan World Bank (1944), General Agreement on Trade and Tariff/GATT (sekarang World Trade Organization/WTO) pada tahun 1948, Washington Consensus (1989), hingga pakta pertahanan seperti NATO (1949). Pada dasarnya, metode-metode politis tersebut berfungsi untuk mengamankan kepentingan AS dan sekutunya, sekaligus menghadang meluasnya doktrin komunisme ke dunia itu. Salah satu buktinya terlihat dalam bidang ekonomi di mana rezim WTO (berdiri 1 Januari 1995) yang kini beranggotakan atas 128 negara anggota jelas merupakan kelompok eksklusif masyarakat internasional yang memberikan hak-hak istimewa kepada negara-negara anggotanya seperti pembukaan hubungan dagang antarnegara anggota, penghapusan/peminimalisasian bea masuk impor, beserta kewajiban negara anggota berupa syarat-syarat keanggotaan yang tentunya tidak ringan.[1]
Sejak tahun 1991 pascakeruntuhan Uni Soviet, struktur politik global berubah total. Dunia sudah tidak lagi terbagi atas dominasi blok barat atau pun blok timur. Negara-negara kapitalis dengan Amerika Serikat sebagai garda terdepannya, dalam banyak aspek tampak berhasil ‘mengepung’ dan menyudutkan negara-negara komunis-sosialis yang tersisa, termasuk Republik Rakyat China (RRC) tanpa kecuali. Hal yang mengejutkan adalah bahwa Republik Rakyat China (RRC) yang sebelumnya diramalkan bakal kolaps mengikuti jejak sekutu utamanya, Uni Soviet, justru malah ‘memeluk erat-erat’ rezim internasional seperti WTO yang notabene ‘rekayasa’ AS beserta para sekutunya, dan menciptakan prestasi fenomenal di kalangan dunia internasional. Dalam dinamikanya, China yang baru saja berhasil menjadi tuan rumah Olimpiade Agustus 2008 lalu di Beijing dengan pembiayaan even yang terbesar sepanjang sejarah pesta olimpiade[2] dan mengirimkan astronotnya untuk melakukan space-walk (2008), tampak sangat ‘nyaman’ dengan keanggotaannya di berbagai rezim internasional dengan tumpukan cadangan devisa sebesar 1,81 trilyun USD hingga Oktober 2008,[3] dan relatif aman dari krisis finansial global yang terjadi baru-baru ini. Kontras sekali keadaannya dibandingkan AS dan negara-negara barat lain yang sibuk menggelontorkan dan menghimpun dana dalam aksi bail-out beramai-ramai demi menyelamatkan sistem finansialnya.[4]
Dikaji dari sudut pandang teori hubungan internasional, dalam menyikapi prestasi fenomenal China itu pertanyaan-pertanyaan kritis yang terbentuk, antara lain adalah:
1. Bagaimana proses keterlibatan China dalam rezim internasional seperti WTO?
2. Bagaimana China sukses mengawinkan antara kepentingan nasional/national interest-nya dan warisan ideologi komunisme-sosialisme oleh ketua Mao (毛泽东 Mao Zedong) 60 tahun silam?
3. Sampai sejauh mana pendekatan liberalis dapat memandang contoh kasus China ini, terutama terkait keanggotaannya dalam WTO?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi landasan pembahasan makalah.
II. Sejarah Singkat Hubungan China dan WTO
Sebelumnya, perlu disepakati terlebih dahulu bahwa diksi “China” dalam praktik sehari-harinya bersifat kontekstual. [5] Namun, dalam makalah ini sebagian besar diksi “China” mengacu pada RRC (China daratan).
Pada tahun 1948 ketika daratan China masih dikuasai oleh Partai Nasional China/PNC (国民党 Guomindang), hubungan antara China dan rezim internasional sudah dimulai. Saat itu, Republik China (ROC) yang berkiblat kepada AS terlibat langsung dalam proses perdagangan bebas melalui pembentukan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) tanggal 19 Mei 1948. Sejak saat itu, era perdagangan bebas global rekayasa AS bersama para sekutunya secara resmi telah dimulai. Peran GATT secara resmi digantikan oleh World Trade Organization (WTO) pada tanggal 1 Januari 1995. WTO merupakan suatu rezim perdagangan global yang bernaung di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa/PBB yang menganut aturan perdagangan bebas yang kurang lebih sama dengan apa yang GATT punya; Bedanya terdapat pada revisi secara teoritis mengenai aturan-aturan baku pada badan tersebut.[6]
Setelah kaum komunis China merdeka pada tahun 1949, pemerintahan Taiwan mengumumkan pengunduran diri dari keanggotaan GATT pada tanggal 5 Maret 1950. Tidak lama setelah Taiwan memisahkan diri dari pemerintahan Beijing, Taiwan mengajukan lamaran sebagai peninjau dalam GATT. Lamaran tersebut disetujui, namun pada tahun 1971 Taiwan dikeluarkan dari GATT karena kebijakan PBB yang mengubah status dan kedudukan Taiwan di PBB. Alasan politis semacam ini dilatarbelakangi oleh kepentingan PBB terhadap RRC yang memandang bahwa pemerintahan China yang resmi adalah pemerintahan di bawah kepemimpinan PKC, terlebih karena China adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Walaupun Taiwan sudah dikeluarkan dari keanggotaan GATT, China belum tertarik untuk menjadi anggota GATT, terutama akibat meletusnya Revolusi Kebudayaan (文化革命 wenhua geming) di China pada periode 1966-1976 yang dicetuskan oleh Ketua Mao.[7]
Setelah Deng Xiaoping 鄧小平 dari kubu reformis menduduki posisi puncak pemerintahan China pada tahun 1976, China membuka dirinya terhadap dunia luar dengan menerapkan Reformasi Pintu Terbuka (gaige kaifang). Kemudian China mulai bergabung dengan organisasi-organisasi ekonomi internasional, seperti World Bank International Monetary Fund (Desember 1945), dan lain-lain. Ambisi dan semangat berapi-api China untuk meneruskan agenda gaige kaifang membuatnya semakin terdorong untuk bergabung kembali dengan GATT. Oleh karena itu, pada tahun 1980 China mengajukan diri sebagai anggota peninjau GATT. Lamaran tersebut baru disetujui dua tahun sesudahnya.
Pada tahun 1986, RRC mengajukan lamaran diri sebagai anggota penuh GATT. Sebagai langkah awal, kedua pihak (China dan GATT) menyiapkan beberapa hal. RRC menyerahkan memorandum tentang kondisi perdagangannya. GATT sendiri pada tahun 1987 membentuk kelompok kerja untuk China yang bertugas meneliti perdagangannya dan menyusun aturan-aturan protokol mengenai hak-hak dan kewajiban China dalam GATT. Akan tetapi, semua persiapan yang telah dibangun oleh kedua pihak selama kurang lebih tiga tahun menjadi mubazir karena terjadi peristiwa Tian’anmen pada tanggal 4 Juni 1989.[8]
Pada tahun-tahun setelah 1992, sistem perekonomian dan pembangunan nasional China sekali lagi mengalami banyak pembaharuan, terlebih setelah adanya peristiwa bersejarah yang dikenang rakyat China sebagai “ucapan nanxun”.[9] Gebrakan Deng ini mengakibatkan perubahan drastis dalam sistem perdagangan dan permodalan China. Perdagangan luar negeri mengalami peningkatan yang signifikan. Hal serupa juga dirasakan pada sektor investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI). Dengan pembaharuan sistem perekonomiannya tersebut, China aktif kembali dalam mengajukan lamaran keanggotaan GATT.
Pada tanggal 1 Januari 1995 WTO menggantikan peran GATT. Secara otomatis, kelompok kerja untuk China saat itu berada di bawah naungan WTO. Kelompok kerja inilah yang mengeluarkan beberapa persyaratan untuk China terkait proses integrasinya dengan WTO.[10]
China merasa persyaratan-persyaratan tersebut terlalu berat baginya sehingga mulai kehilangan gairah untuk bergabung dengan WTO, bahkan sempat mengumumkan tidak ingin lagi melakukan perundingan bilateral dengan WTO. Namun, semua hal tadi mulai berubah sejak berakhirnya Perang Dingin. Amerika Serikat menyatakan akan mendukung lamaran RRC sebagai anggota WTO. Dari segi ekonomis, hal ini dilakukan AS dengan pertimbangan rasional bahwa China merupakan pasar yang sangat besar (seperlima penduduk dunia) dan sangat potensial bagi bermacam-macam produk barang dan jasanya. Akhirnya setelah melalui berbagai perundingan yang alot, pada tanggal 17 September 2001 WTO menyetujui permohonan keanggotaan RRC dalam WTO. Setelah itu, pada saat konferensi Menteri WTO di Doha, Qatar tanggal 10 November 2001, perjanjian antara China dan WTO diresmikan. Dan sebulan setelah itu, tepatnya tanggal 11 Desember 2001, China dinyatakan secara resmi sebagai salah satu negara anggota WTO.
III. Latar Belakang dan Tujuan China Menjadi Anggota WTO
Pada awalnya, pertimbangan dan tujuan China menjadi anggota WTO adalah alasan ekonomis semata, yakni sebagai wahana untuk mencapai akselerasi industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. China menginginkan pembukaan pasar global sehingga produk-produk ekspornya bisa masuk dan sekaligus investasi asing bisa menggairahkan perekonomian negara yang dikatakan berada pada tahap awal sosialisme itu.[11] Beberapa tujuan konkret China atas keanggotaannya di WTO, antara lain:
1. Mempermudah ekspor Cina ke negara-negara anggota WTO lainnya, terutama pasar AS dan Uni Eropa;
2. Menghapus batasan perdagangan dan memperluas akses pasar bagi barang-barang domestik dan luar negeri;
3. Mencapai industrialisasi secara cepat (revolusi industri) dan alih teknologi negara maju;
4. Meningkatkan pendapatan dalam negeri dari sektor ekspor dan investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI); dan
5. Memperoleh prestise di mata dunia internasional.
Khusus mengenai poin kelima ini, meminjam istilah yang dikemukakan sinolog I. Wibowo, China juga akan menikmati “keuntungan kasat mata/intangible benefits” melalui jalur keanggotaan WTO. [12]
Berikut beberapa keuntungan konkret yang sudah dinikmati China setelah bergabung dengan WTO, antara lain:[13]
1. Hingga tahun 2002, China memiliki hubungan dagang bebas dengan 127 negara anggota WTO lainnya;
2. Peningkatan industrialisasi China dan alih teknologi tingkat tinggi berhubung semaking terbukanya investasi asing;
3. Penghargaan yang semakin tinggi terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI), hak paten produk/trademark, dll sehingga rakyat China bisa lebih kreatif, inovatif, dan berkompetisi secara sehat dalam sistem yang melindungi karyanya;
4. Otoritas dan rakyat China di satu sisi diuntungkan oleh pemasukan berbagai jenis pajak baru dan arus investasi asing yang masuk;
5. Semakin meningkatkan sumber daya manusia (SDM) rakyat China, dan lain-lain.
IV. Mengkaji Kesuksesan China dalam Rezim Internasional
WTO merupakan salah satu rezim internasional yang dituding negatif oleh banyak pihak karena terlalu menguntungkan kepentingan negara-negara maju, dan merugikan negara-negara berkembang yang mayoritas ‘gagap’ berkompetisi karena kalah bersaing dalam hal modal, teknologi, arus informasi, lintas jasa, SDM, dan lain-lain.[14] Tidak hanya itu, pada pandangan ekstrem rezim-rezim global seperti IMF dan World Bank dianggap sebagai ‘serigala berbulu domba’ yang cenderung membuka dunia ketiga demi kepentingan negara-negara maju, daripada tujuan dasarnya mengurangi tingkat kemiskinan global.[15] Namun, kartu ini ternyata berhasil dimainkan China, dan China tidak ‘tenggelam’ dalam alur permainan rezim WTO. Sejauh mana teori HI dapat memandang fenomena ini?
Pada dasarnya, menurut hemat saya keberhasilan China dalam memanfaatkan tantangan globalisasi setidaknya dapat dipandang dalam dua pendekatan, yaitu:
1. Menurut pendekatan liberalis; dan
2. Peran kubu reformis dalam decision-making Partai Komunis China.
IV.I. Perspektif Liberalis dalam Memandang China dan WTO
Definisi “rezim”, antara lain:
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “rezim” adalah tata pemerintahan negara; pemerintahan yg berkuasa.[16]
- Sedangkan, dalam bidang politik rezim berarti bentuk pemerintahan; seperangkat aturan, norma-norma sosial atau kebudayaan yang mengatur jalannya suatu pemerintahan dan interaksinya dengan masyarakat.
- Dalam studi Hubungan Internasional ada satu pendekatan utama terkait rezim ini, yakni pendekatan liberalis. Menurut tradisi liberalis, contohnya seperti yang dikemukakan Robert Keohane, rezim/institusionalisasi yang dilandasi oleh kerja sama adalah “Institutions possesing norms, decision rules, and decisionmaking procedures which facilitate a convergence of expectations.”[17]
Tabel 1
Pandangan dasar tradisi pluralisme/liberalisme dalam Teori Hubungan Internasional
| No. | Dasar asumsi | Perspektif Liberalisme/Pluralisme |
| 1. | Unit analisis | Aktor negara dan aktor nonnegara sama pentingnya |
| 2. | Cara pandang aktor | Aktor negara dipecah ke dalam beberapa komponen, beberapa di antaranya dapat bertindak secara transnasional |
| 3. | Dinamika perilaku aktor | Pembuatan kebijakan luar negeri dan proses-proses transnasional melibatkan konflik, tawar-menawar, koalisi, dan kompromi |
| 4. | Isu utama | Sosial ekonomi, tingkat kesejahteraan, dll yang dianggap lebih penting daripada isu keamanan nasional semata |
Sumber: Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, (New York: Macmillan Publishing Company, 1993), hlm. 10.
Seperti yang dijabarkan Keohane, pendekatan liberalis dalam memandang rezim menekankan tentang pentingnya keberadaan rezim/institusi (di luar aktor negara) yang dapat memengaruhi aktor negara/aktor-aktor internasional lainnya (perspektif negara/state sebagai nonsatu-kesatuan aktor/non-unitary unit yang bisa dipecah). Asumsi dasarnya adalah bahwa bentuk kerja sama antarnegara merupakan norma/etika/value yang mendasari pencapaian kepentingan/national interest-nya. Dapat dikatakan, rezim menurut perspektif liberalis adalah bentuk kerja sama internasional.
Sesuai dengan definisi dasarnya, rezim mencakup berbagai bentuk isu internasional, dan biasanya satu rezim terfokus pada satu isu tertentu dengan anggota-anggota yang tidak hanya terdiri dari negara.
Berangkat dari pendekatan interest-based liberalis, dalam konteks ini dikatakan bahwa WTO bisa berjalan tanpa satu kekuatan hegemon tertentu sebab terdapat “convergence of expectations” atau yang saya interpretasikan sebagai “ekspektasi/harapan dari masing-masing konstituen rezim yang terkumpul dalam satu wadah pertemuan”. WTO sebagai rezim memfasilitasi kerja sama dengan menciptakan standar-standar tertentu bagi para anggotanya. Ketika semua anggota negara berharap agar partisipan lain bekerja sama maka kemungkinan melangsungkan kerja sama secara konstan dapat terus meningkat. Jadi, tidak sepenuhnya benar dikatakan bahwa konflik adalah dasar dari sistem anarki dunia yang diyakini oleh kaum realis. Kaum neoliberal sendiri mengatakan bahwa para realis mengabaikan suatu tahap di mana negara-negara bersedia berbagi kepentingannya dengan negara lain, dan memiliki sifat hubungan/interaksi internasional yang dilakukannya berulang-ulang kali.
Terkhusus mengenai kesuksesan China dalam rezim internasional, pendekatan liberalis dalam teori rezim merupakan salah satu kunci dalam menjelaskan kepragmatisan China. China sebagai aktor negara tidak menyangkal adanya bentuk kerja sama internasional, terutama dalam bidang ekonomi, bahkan dengan rezim terdiktator di dunia sekalipun, seperti beberapa negara di Afrika.[18] Hal ini yang tidak akan dilanggar oleh perusahaan multinasional (MNC) AS atau Uni Eropa ‘seliberal’ apa pun. Negara-negara barat, terutama AS sangat kegerahan dengan politik luar negeri nasionalis-pragmatis China itu. Berkali-kali presiden Hu Jintao mengelak dari tudingan-tudingan negatif dengan mengeluarkan jargon-jargon seperti “Tanpa syarat politik apa pun, murni kepentingan bisnis” hingga jargon “hexie shijie atau hexie shehui (masyarakat dunia yang harmonis)”. Agen-agen pembangun ekonomi China tersebar ke seluruh dunia, seringkali tanpa pandang bulu latar belakang mitra bisnisnya. Mereka tidak terlalu ambil pusing dengan embel-embel seperti “demokrasi” yang diusung AS selama ini. Semangat pragmatis China dalam mengejar kekayaan dan kemuliaan (termasuk prestise di mata internasional) terpatri dalam-dalam di hati rakyat China.
Sebenarnya, pengadopsian ideologi dan sistem yang serba baru ini sudah tercermin dari tiga ujaran populer oleh Deng Xiaoping sejak dua dekade lalu, yaitu “sosialisme tidak berarti kemiskinan, sosialisme justru melenyapkan kemiskinan”, “tidak peduli kucing hitam atau putih, selama dia bisa menangkap tikus”, dan “zhi fu shi guangrong (menjadi kaya itu mulia)”. Dengan dasar-dasar fundamental itu, arah politik domestik dan internasional China kemudian berubah total, khususnya setelah tahun 1978. Dalam dinamikanya, di satu sisi pemerintah China tetap memegang kontrol makro (hongguan tiaokong) dan membangun kerja sama internasional dengan siapa saja yang penting bagi national interest-nya, dan di satu sisi menghalalkan (bahkan mendorong) praktik kapitalisme di negaranya.[19]
Contoh konkret lain dapat kita lihat ketika China merapatkan kerja sama bilateral secara ekonomi dengan Taiwan. Tanggal 3 November 2008 akan dikenang sebagai hari yang bersejarah bagi rakyat China dan Taiwan ketika Chen Yunlin dan Ma Ying-jeou untuk kali pertama bertemu secara diplomatik setelah sejarah 60 tahun yang kelam bagi hubungan bilateral kedua negara.[20] Pada hari itu juga, China dan Taiwan sepakat untuk tidak membicarakan isu politik, dan membuka kerja sama ekonomi seperti penambahan jalur penerbangan reguler, layanan pos langsung, penerbangan kargo langsung, isu keamanan produk pangan, hubungan perkapalan, dll.
Akan tetapi, pendekatan liberalis dalam konteks ini bukan tanpa kelemahan. Pemerintah China adalah aktor negara/state actor yang sangat dominan dalam hampir semua aspek. Bahkan semua perusahaan multinasional (mayoritas adalah BUMN) yang menjadi ujung tombak dan agen pembangunan ekonomi bukan milik swasta (dikendalikan secara ketat oleh negara).[21] Pendekatan liberalis dalam teori rezim dan cara memandang kesuksesan China hanya terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan indikator kepragmatisan China dalam memperjuangkan national interest-nya, serta variabel penjelas dalam perspektif liberalis yang memecah otoritas China menjadi beberapa unit yang dapat dipengaruhi pihak-pihak lain. Dalam konteks kesejarahannya, ada tendensi bahwa China melawan kekuatan barat dengan ala barat juga, sesuatu yang sudah lazim terjadi bahkan sejak sistem dinasti/kekaisaran China tumbang.[22]
Apabila ditanyakan, apakah benar bahwa rezim itu (WTO) memengaruhi otoritas China? Jawaban saya adalah iya. Tapi hingga sejauh mana? Perlu digarisbawahi bahwa terdapat derajat kepentingan tertentu antara rezim internasional dan state ini. Bagi China, seperti yang telah saya kemukakan sebelumnya, WTO hanya sebatas kendaraan yang memfasilitasi politik luar negeri dan national interest-nya. China mungkin bersedia tunduk pada standar-standar yang ditetapkan WTO, tapi China yang hingga saat ini dianggap tidak patuh penuh kepada WTO (uneven and incomplete),[23] ternyata memiliki ambisi sendiri untuk mengubah rezim WTO ‘dari dalam’ sesuai dengan kepentingan China. China yang ditekan oleh anggota WTO lain, terutama AS, tidak akan-akan terburu-buru ‘taat’ pada tekanan AS atau negara mana pun. Bukan tidak mungkin, China yang kekuatan ekonominya semakin meraksasa dari waktu ke waktu dapat merapatkan barisan negara-negara berkembang dalam memengaruhi pembuatan pasal-pasal WTO yang selama ini selalu didikte oleh negara-negara maju.[24]
Sedangkan bagi WTO yang dengan catatan didominasi oleh negara-negara maju (AS, Uni Eropa, dan Jepang), pertimbangan awal memasukkan China ke dalam keanggotaan WTO adalah agar mereka dapat menikmati barang-barang ekspor China yang sangat murah dan juga, potensi konsumen China yang jumlahnya masif itu akan gencar membeli produk-produk impor. Para investor asing juga mengincar kemungkinan memproduksi produk-produk low-cost di dalam China yang dapat diekspor dan dibuang ke pasar domestik. Dari segi politis, pemerintah asing memiliki motif tersendiri atas keanggotaan China di WTO. Mereka berharap bahwa dengan mengintegrasikan China ke dalam rezim perdagangan secara formal dan juga rezim investasi, China akan duduk pada landasan yang sama sehingga aneka pertikaian/persengketaan dapat diselesaikan dengan mudah. Kecuali itu, China akan didorong untuk menjalankan sistem undang-undang ekonomi yang lebih transparan. Amerika Serikat, secara khusus, berharap bahwa dengan integrasi China ke dalam ekonomi dunia, China juga akan mengalami perubahan dalam sistem politiknya. Keterbukaan ekonomi akan mendukung lahirnya demokrasi. Demikian kira-kira alur argumen mereka.[25]
IV.II. Peran Kubu Reformis dalam Pembangunan China Moderen
Kaum reformis dalam Partai Komunis China memainkan peranan penting terkait semangat kapitalisme China, dan pada akhirnya berujung ke proses integrasi China ke masyarakat internasional.
Dalam sejarah China kontemporer, pionir terkemuka dari kubu reformis adalah Deng Xiaoping (1904-1997). Deng sukses duduk di puncak panggung kekuasaan China setelah berhasil meyakinkan Politibiro PKC sekaligus rakyat China dengan agenda-agenda pembaharuannya, tapi tetap memegang dasar-dasar dan pedoman komunisme-sosialisme. Meskipun hingga sekarang selalu timbul perdebatan panas di antara para petinggi PKC dan para sinolog tentang keabsahan ideologi komunis-sosialis China, contoh konkret seperti kendali ekonomi nasional makro (hongguan taikong) yang masih digunakan China merupakan salah satu dari segelintir warisan komunis-sosialis bagi China moderen.
Evolusi Ideologi China 1978-2003 [26]
| Periode | Dasar ideologi dan dinamikanya |
| 1978-1987 | Komunisme |
| 1987 | Konggres XIII mengesahkan “sosialisme tahap awal” |
| 1992 | Konggres XIV mengesahkan “Teori Deng Xiaoping” |
| 1993 | Sidang pleno III, “ekonomi pasar sosialis” |
| 1997 | Konggres XV: “Sosialisme tahap awal” ditegaskan sekali lagi |
| 1999 | Amandemen Pasal 11, UUD 1982, mengakui hak milik swasta |
Kubu reformis China yang diprakarsai Deng itu merupakan para pemikir dan penggiat utama dari nafas baru China. Perjalanan kubu reformis dalam meyakinkan Politbiro PKC dan rakyat China tidaklah mulus. Deng, misalnya, pernah mengalami proses ‘pembelajaran kembali nilai-nilai komunis-sosialis’ (dikucilkan ke desa pedalaman selama bertahun-tahun) karena dianggap terlalu ‘kapitalis’ oleh ketua Mao (Mao Zedong). Setelah Mao mangkat, Deng kembali ke jajaran PKC, dan berhasil mengubah pendirian Partai dengan dalil-dalil yang dikembangkan oleh Mao sebelumnya.[27]
Berangkat dari dasar pembangunan ekonomi, para reformis China kemudian secara bertahap ‘memodifikasi’ dasar ideologis negara, Deng meletakkan landasan bagi pembangunan China moderen. Ini dapat dilihat dari tabel tentang ringkasan evolusi sistem ekonomi China yang terkenal itu:
Tabel 3
Evolusi Sistem Ekonomi China
| Periode | Sistem Ekonomi |
| 1978-1979 | Ekonomi terencana |
| 1979-1984 | Ekonomi terencana didampingi dengan regulasi pasar |
| 1984-1987 | Ekonomi komoditas terencana |
| 1987-1989 | Ekonomi di mana negara mengatur pasar dan pasar mengatur perusahaan |
| 1989-1991 | Ekonomi dengan integrasi organis antara ekonomi terencana dan regulasi pasar |
| 1992 | Ekonomi pasar sosialis dengan ciri khas China |
| 1994 | Reformasi di bidang hak milik (property rights) |
Sumber: Fan Gang, “Reform and Development: the Dual-Transformation of China,” dlm. Pamela C.M. Mar dan Frank-Jurgen Richter, China: Enabling A New Era of Changes (Singapore: John Wiley&Sons, 2003), hlm. 37.
Terkhusus mengenai keanggotaan China dalam rezim WTO, kubu reformis yang beberapa tahun silam dipimpin mantan presiden Jiang Zemin (periode 1989-2002) memakai “kartu WTO” untuk menekan kelompok lawan “konservatif”. Dengan memakai tekanan dari luar, mereka berharap dapat mendorong diterapkannya ekonomi pasar secara lebih konsisten di China.[28]
Setelah menelaah unit pemerintahan China, saya akan beranjak ke dalam analisis isu. Para ideolog dan decision-maker PKC masa pascaDeng menyandarkan diri pada teori pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi (economic growth) yang sangat populer di seluruh dunia saat ini. Pemimpin China, termasuk mantan PM Zhu Rongji (periode 1998-2003) terus-menerus menekankan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% sebagai patokan yang tidak boleh diubah-ubah. Ini dikemas dalam sebuah konsep “xiao kang” yang tidak lain adalah konsep pembangunan atas dasar pertumbuhan ekonomi. [29]
Teori economic growth merupakan teori yang dikritik banyak pihak seperti kaum sosialis dan environmentalist karena sifatnya yang sangat destruktif. Apa yang membuat para petinggi China menganut jalan ini, dan terutama dalam konteks makalah ini bergabung dengan WTO? Seperti yang dikemukakan I. Wibowo dalam bukunya, pilihan China tersebut erat kaitannya dengan tren dunia kini, yaitu economic legitimation. Kegagalan dan kesuksesan sebuah pemerintahan di mana-mana diukur dengan berhasil-tidaknya pemerintah itu berhasil membawa kemakmuran material kepada rakyatnya. Hanya pemerintah yang mampu memakmurkan rakyatnya yang mendapatkan legitimasi. Hal ini tidak hanya berlaku di negara-negara maju (Eropa, Jepang, AS), tetapi juga di negara-negara yang sedang berkembang (Thirld World Countries). Pemerintah negara-negara dunia berusaha mati-matian mendatangkan kemakmuran material kepada rakyatnya sebagai dasar legitimasinya.[30] Dengan kata lain, pendekatan liberalis dalam memahami developmental state ala China sudah tepat tentang pentingnya isu ekonomi dalam pengkajian kepentingan nasional, di samping peran isu keamanan strategis semata.
Hanya saja, pendekatan ini bukanlah tanpa celah atau kelemahan. Dengan adanya krisis finansial global seperti sekarang, superstruktur teori Hubungan Internasional (dalam hal ini pendekatan liberalis) sedang diuji keabsahannya. Pendekatan liberalis yang sebagian besar diadopsi dan diaplikasikan melalui praktik neoliberalisme menghadapi tantangan baru di mana segenap aktor yang terlibat di dalamnya harus menyesuaikan koordinasi antara peran negara dan tentunya, mekanisme pasar itu sendiri. Dalam konteks China, tidak tertutup kemungkinan bahwa konsep “sosialisme yang bercirikan China” itu kemudian dirombak/disesuaikan lagi. Rezim WTO pun sedang menghadapi tantangan baru. Peran negara-negara berkembang dalam level rezim internasional semakin menguat. Tidak cukup hanya negara-negara maju yang aktif berperan dan mendominasi sistem.[31]
V. Kesuksesan Kubu Reformis China
Setelah lama terkungkung oleh ketakutan akan “bahaya kapitalisme” seperti yang didoktrinkan oleh dalil-dalil komunisme-sosialisme, periode pasca gaige kaifang membuat rakyat China menjelma menjadi rakyat yang mengejar kemuliaan dan keagungan di semua lini, baik dalam lingkup domestiknya, maupun di kancah internasional. Para decision-makers China yang didominasi kaum reformis, setali tiga uang. Kebijakan-kebijakan yang diambil pun seringkali menyimbolkan semangat kapitalisme China. Salah satunya dengan masuk ke dalam WTO.
Keanggotaan China di WTO merupakan salah satu proses integrasi internasionalisasi China yang bersejarah dan monumental, baik bagi masyarakat internasional maupun rakyat China sendiri. Dinamika keanggotaan China dalam WTO seringkali diwarnai oleh tekanan internasional (terutama AS) karena China belum sepenuhnya tuntuk pada standar-standar WTO, dan China diyakini memiliki ambisi/motif sendiri terkait keanggotaannya itu. Aspek-aspek tersebut tentu sangat menarik untuk kita cermati. Saat ini China justru merengkuh globalisasi dengan semangat kapitalismenya. Seperti yang ditandaskan I. Wibowo dalam bukunya, budaya komunisme-sosialisme dengan segala ciri altruistiknya sudah hampir terlupakan oleh rakyat China. Kini, semangat nasionalisme China dibangun atas dasar lain yang sangat sensitif bagi mereka pada tahun-tahun silam, yakni mengejar keagungan yang pada praktiknya adalah kapitalisme (terkontrol).[32]
Keadaan menjadi semakin kompleks akibat krisis finansial global yang terjadi belakangan ini. “Washington Consensus” yang selama ini diusung Amerika Serikat justru mengisyaratkan akan adaya koreksi atas mekanisme pasar kapitalis-liberal yang selama ini berjalan ‘terlalu liberal’. Bagi kubu China yang masih menjalankan konsep developmental state, ini adalah sinyal positif bagi keberhasilan kaum reformis China dalam menjalankan agenda reformasinya.
Daftar Pustaka
Bacaan Primer
Brahm, Laurence J. - (ed). China After WTO. Beijing: China Intercontinental Press. (2002).
Brahm, Laurence J. China’s Century: The Awakening of the Next Economy Powerhouse. Singapore: John Wiley&Sons. (2001).
Far Eastern Economic Review. (Oktober 2003).
Jhamtani, Hira. WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga. Yogyakarta: Insistpress. (2005).
Journal of Contemporary China, Vol. 7, No. 17. (Maret 1998).
Keohane, Robert. O. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. United Kingdom: Princeton University Press. (1985).
Li, Cheng. China’s Leaders: The New Generation. Oxford: Rowman&Littlefield Pub. (2001).
Mar, Pamela C.M. dan Richter, Frank-Jurgen. China: Enabling A New Era of Changes. Singapore: John Wiley&Sons. (2003).
Panitchpakdi, Supachai dan Clifford, Mark L. China and the WTO. Singapura: John Wiley&Sons. (2002).
Pearson, Margareth M. China Joins the World. New York: Concil on Foreign Relations Press. (1999).
Viotti, Paul. R. dan Kauppi, Mark V. International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism - 2nd ed. New York: Macmillan Publishing. (1993).
Bacaan Sekunder
Alwi, Hasan (pemimpin tim redaksi). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. (2002).
Fathers. Michael dan Cottrell, Robert. Pembantaian Tian’anmen – (terjemahan). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. (1990).
Fishman, Ted C. China Inc. - (terjemahan). Jakarta: Elex Media Komputindo. (2006).
Griffiths, Martin dan Callaghan, Terry O’. IR: The Key Concepts. London&New York: Routledge. (2002).
Lam, N. Mark dan Graham, John L. China Now – (terjemahan). Jakarta Elex Media Komputindo. (2007).
Moore, Mike. A World Without Walls: Freedom, Development, Free Trade and Global Governance. Cambridge University Press. Cambridge: 2003.
Navarro, Peter. Letupan-Letupan Perang China Mendatang – (terjemahan). Jakarta: Elex Media Komputindo. (2008).
Pustaka Web
[1] Martin Griffiths dan Terry O’ Callaghan, IR: The Key Concepts, (London&New York: Routledge, 2002), hlm. 338-341.
[2] 45 milyar USD, bahkan ada yang memperkirakan mencapai 70 milyar USD lih. http://financialexpress.com/news/beijing-olympics-have-been-most-expensive-so-far/348024
[3]http://kompas.co.id/read/xml/2008/10/27/00262913/perekonomian.as.akan.makin.bergantung.ke.china dan Kompas, 9 Oktober 2008, “Peran China Dinantikan untuk Mengatasi Krisis”, hlm. 15.
[4] http://kompas.com/read/xml2008/10/08/13240127/waspada.bailout.tak.efektif.krisis.di.as.berlanjut
[5] Kaum Komunis China (共产党 gongchandang) pimpinan Mao Zedong memenangkan kekuasaan atas China daratan pada tahun 1949. Akibatnya, Partai Nasional China/PNC (国民党 guomindang) yang saat itu dipimpin Chiang Kai-sek melarikan diri ke Pulau Formosa (Taiwan). Sejak saat itu, keduanya mendirikan pemerintahannya masing-masing; Pimpinan Mao di China daratan, dan pimpinan Chiang Kai-sek di Taiwan.
[6] WTO merupakan organisasi internasional dengan sistem penyelesaian sengketa yang kuat, sementara GATT hanya kesepakatan antarpemerintah. WTO mengatur liberalisasi perdagangan produk manufaktur, pertanian, dan jasa melalui produk hukum seperti General Agreement on Trade in Services (GATS), Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), dan penanaman modal melalui Trade Related Investment Measures (TRIMs).
[7] Mao Zedong mengumumkan gerakan revolusi proletariat di China. Semua akar kebudayaan China yang umurnya ribuan tahun itu kecuali bahasa Mandarin, harus diganti total dengan kebudayaan komunisme-sosialisme. Segala macam praktik kapitalisme diharamkan di daratan China.
[8] Pemerintah China meredakan demonstrasi prodemokrasi besar-besaran, korban sipil yang berjatuhan lebih dari 1.000 orang. Peristiwa ini membuat China dikucilkan oleh masyarakat internasional. Salah satu eksesnya, permohonan China untuk menjadi anggota penuh GATT ditolak. Salah satu literatur yang secara ‘gamblang’ membahas peristiwa ini lih. Michael Fathers dan Robert Cottrell, Pembantaian Tian’anmen – (terjemahan), (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990).
[9] ‘Ucapan perjalanan ke selatan’: Gebrakan Deng Xiaoping dalam meneruskan program gaige kaifang ketika politik domestik China stagnan dan ada tendensi bahwa China kembali dipegang oleh kubu konservatif. Teori Deng yang dikenal sebagai “Deng Xiaoping lilun” menegaskan kembali pembaharuan China, dan disahkan dalam Kongres PKC XIV (Oktober 1992) sebagai landasan pembangunan China moderen.
[10] Persyaratan itu antara lain, seperti transparansi menyeluruh dalam aturan perdagangan, penjadwalan pasti atas rencana penurunan hambatan tarif, perlakuan yang sama atas produk domestik dan produk luar negeri, penghapusan sistem penetapan harga oleh negara, penjadwalan atas penghapusan subsidi industri, adanya mekanisme perlindungan bagi negara anggota WTO terhadap perubahan drastis ekspor RRC, menunjukkan kemampuan memenuhi persyaratan WTO secara menyeluruh dan merata ke seluruh wilayah RRC sehingga wilayah pedalaman sama terbukanya dengan Wilayah Ekonomi Khusus, perlindungan HAKI, dll.
[11] Wacana “shehui zhuyi chuji jieduan” atau “sosialisme pada tahap awal” dikemukakan dalam Konggres PKC XIII (1987) untuk mengakomodasi kemacetan ideologis kaum konservatif dan reformis China dalam membangun China moderen.
[12] I. Wibowo, Belajar dari China, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), hlm. 63. Maksud dari pernyataan ini adalah China percaya bahwa prestise negaranya akan naik di mata internasional dan memperkuat legitimasinya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terutama dalam kerangka persaingannya dengan Taiwan dan dengan kubu konservatif di dalam pemerintahan internalnya.
[13] Diolah dari Laurence J. Brahm, China After WTO, (Beijing: Intercontinental Press, 2002).
[14] Lih. Hira Jhamtani, WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga, (Yogyakarta: Insistpress, 2005), terutama Bab II: Pertarungan Tak Seimbang.
[15] Martin Griffiths dan Terry O’Callaghan, op.cit., hlm. 334.
[16] Hasan Alwi (pemimpin tim redaksi), Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 954.
[17] Robert O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, (United Kingdom: Princeton University Press, 1984), hlm. 59.
[18] China bahkan dituding melakukan praktik neoimperialisme di Afrika lih. Peter Navarro, Letupan-Letupan Perang China Mendatang, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 95-110.
[19] I. Wibowo, op.cit., terutama Bab III: China Sudah Berubah Menjadi Kapitalis?
[20] Untuk kali pertama dalam sejarah moderen, para petinggi terkemuka China dan Taiwan bertemu, dan menandatangani perjanjian di bidang ekonomi, lih.
http://kompas.co.id/read/xml/2008/11/0313093357/china-taiwan.akhirnya.berunding
[21] China masih menerapkan sistem “dua kendali” dalam perusahaan-perusahaan yang berskala besar, maksudnya CEO perusahaan adalah juga sekaligus sebagai sekretaris PKC. Pembangunan ekonomi China juga didominasi oleh BUMN China. Penjelasan lebih mendalam lih.
[22] Kaum nasionalis China yang dipimpin Sun Yat-sen berhasil menumbangkan sistem monarki, dan diubah dengan sistem republik konstitusional (1911).
[23] Untuk penjelasan lebih lanjut lih., “The One-Two Punch”, Far Eastern Economic Review (2 Oktober 2003), hlm. 26-28.
[24] I. Wibowo, op.cit., hlm. 76-78.
[25] Margaret M. Pearson, “China’s Integration into the International Trade and Invesment Regime”, dlm. Elizabeth Economy dan Michel Oksenberg (eds.), China Joins the World (New York: Council on Foreign Relations Press, 1999), hlm. 166.
[26] Dikutip dari I. Wibowo, op.cit., hlm. 83.
[27] Deng mendorong perubahan China dengan meminjam kata-kata ketua Mao, yakni “shi shi qiu shi” (mencari kebenaran dari fakta). Dalam konteks reformasi saat itu, Deng mendorong rakyat China dan para kader partai untuk mencari “kebenaran”, bukan mencari ideologi atau dogma-dogma partai semata.
[28] I. Wibowo, op.cit., hlm. 74.
[29] Hal ini ditegaskan lagi dalam Konggres Nasional Partai Komunis XVI, November 2002. Sebagai ikhtisar, lih. John Wong, “Xiao-kang: Deng Xiaoping’s Socio-economic Development Target for China,” dlm. Journal of Contemporary China, Vol. 7, No. 17 (Maret 1998), hlm. 141-152.
[30] Gabungan argumen pribadi I. Wibowo, op.cit., hlm. 167-170 dengan tema economic legitimation yang dibahas dalam Juergen Habermas, Legitimation Crisis (London: Heinemann, 1976).
[31] Peran negara-negara berkembang dalam penanganan isu-isu internasional semakin signifikan dan krusial, salah satunya, lih. Kompas, 12 Oktober 2008, “Presiden Bush Akan Ajak G-20”, hlm. 1 dan 15, atau lih. Kompas, 9 Oktober 2008, “Peran China Dinantikan untuk Menghadapi Krisis’, hlm 1 dan 15.
[32] I. Wibowo, op.cit., terutama bab V: “Kapitalisme atau Sosialisme” , hlm. 78-91.





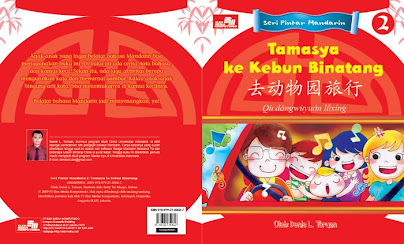
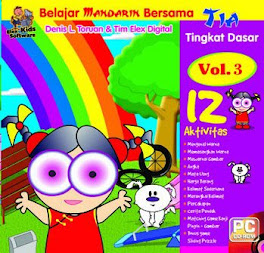
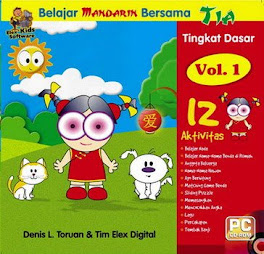
No comments:
Post a Comment