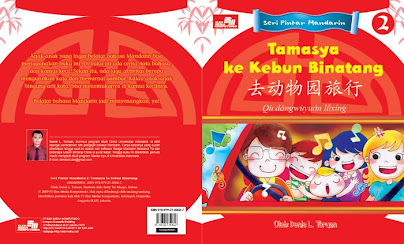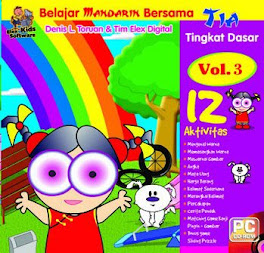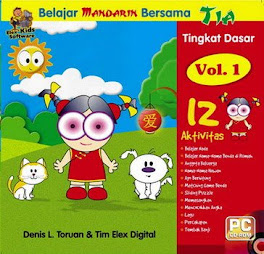From Denis Toruan to you...
02 January 2010
2010 = Chinese New Year
Published: December 31, 2009
It’s the season when pundits traditionally make predictions about the year ahead. Mine concerns international economics: I predict that 2010 will be the year of China. And not in a good way.
Actually, the biggest problems with China involve climate change. But today I want to focus on currency policy.
China has become a major financial and trade power. But it doesn’t act like other big economies. Instead, it follows a mercantilist policy, keeping its trade surplus artificially high. And in today’s depressed world, that policy is, to put it bluntly, predatory.
Here’s how it works: Unlike the dollar, the euro or the yen, whose values fluctuate freely, China’s currency is pegged by official policy at about 6.8 yuan to the dollar. At this exchange rate, Chinese manufacturing has a large cost advantage over its rivals, leading to huge trade surpluses.
Under normal circumstances, the inflow of dollars from those surpluses would push up the value of China’s currency, unless it was offset by private investors heading the other way. And private investors are trying to get into China, not out of it. But China’s government restricts capital inflows, even as it buys up dollars and parks them abroad, adding to a $2 trillion-plus hoard of foreign exchange reserves.
This policy is good for China’s export-oriented state-industrial complex, not so good for Chinese consumers. But what about the rest of us?
Read more @ http://www.nytimes.com/2010/01/01/opinion/01krugman.html
28 June 2009
Peran Negara dan Langkah G-20 dalam Mengatasi Krisis Finansial Global 2008-2009

“…Goverment has a large role to play. The right mix of government and markets will differ between countries and over time... The list of potential arenas for government action is large. Today, nearly everyone agrees that government needs to be involved in providing basic education, ilegal frameworks, infrastructure, and some elements of social safety nets, and in regulating competition, banks, and environmental impacts.”
-Joseph E. Stiglitz1
I. The End of Ortodox Laissez-faire?
Kejatuhan blok timur (komunis) pada awal era 1990-an menandakan berakhirnya rivalitas yang sangat kental (Perang Dingin/the Cold War) antara dua superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keadaan politik global pascaperang dingin menjadi berubah drastis; negara-negara di dunia dihadapkan pada skenario baru di mana satu hegemon tampil dominan dalam perpolitikan global, termasuk dalam bidang ekonomi.2 Pada waktu yang bersamaan, perkembangan kecanggihan teknologi informasi tidak berhenti tidak membalik (maintaining) agenda globalisasi.
Perkembangan politik global pascaperang dingin, khususnya secara ideologis, terdokumentasikan dengan baik salah satunya oleh Francis Fukuyama dalam karyanya yang sangat provokatif dan terkenal, The End of History and the Last Man (1992). Di situ, Fukuyama berargumentasi bahwa kapitalisme-liberalisme keluar sebagai pemenang absolut, dan bahwa proses sejarah manusia itu sendiri dikatakan sudah stagnan/berhenti.3 Dalam konteks clash of rivalry actors, argumen Fukuyama tersebut dapat diterjemahkan ke dalam bahasa realisme HI sebagai Hegemonic Stability Theory4 - AS merupakan satu-satunya hegemon yang masih bertahan pascaperang dingin. Institusi keuangan global (IMF, World Bank) yang ada juga didominasi oleh AS, dan aktivitas perekonomian global pun sedikit banyak mengadopsi model sistem ekonomi pasar. Dengan asumsi dasar seperti itu, dapat disimpulkan untuk sementara bahwa baik secara politik ataupun ekonomi keadaan global dapat berangsur-angsur menjadi lebih baik dibandingkan pada era Perang Dingin dan masa-masa sebelumnya lagi.
Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya - krisis finansial global merebak pada Juli 20075 di mana aktivitas perekonomian dunia berangsur-angsur lesu dan terpuruk, terburuk semenjak terjadinya Depresi Besar pada era 1930-an. Ironisnya, krisis ini justru dimulai/disebabkan oleh non-state actors yang beroperasi dalam cakupan global dan didukung oleh rezim laissez-faire ala Washington Consensus.6 Efeknya berimplikasi global, dan mengakibatkan negara-negara seliberal AS dan Uni Eropa sekalipun untuk mengintervensi pasar dengan memberikan bail-out kepada MNC-MNC mereka beserta paket stimulus untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Negara-negara berkembang juga turut merasakan dampak krisis, dan ‘terjun’ lebih dalam ke dalam mekanisme pasar, antara lain dengan paket stimulus dan inisiatif lainnya untuk menggenjot (dan menjaga) pertumbuhan ekonomi domestiknya. Dalam panggung ekonomi politik internasional, regionalisme negara-negara maju seperti UE contohnya, bersikeras menuntut penataan pergerakan kapital transnasional/global, sementara AS bersikukuh dengan status quo. Asumsi bahwa pasar (market) mengoreksi dirinya sendiri menjadi irelevan seiring berkembangnya zaman.7 Negara-negara dunia, terutama yang tergabung dalam G-20 yang menguasai 80% perdagangan global sepakat bertemu dalam konferensi tingkat tinggi (summit) pada 2 April 2009 di London, Inggris, untuk mencari solusi bersama terkait krisis finansial global. Fenomena ini menggarisbawahi adanya tendensi peran/intervensi negara (secara kolektif) dalam mekanisme pasar domestik maupun global, yang kita tahu bertentangan dengan asumsi dasar liberalisme (laissez-faire).
Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan sederhana ini berusaha mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
- Apa peran negara dalam agenda globalisasi (free-trade), khususnya terkait ekonomi politik internasional?
- Mencermati hasil yang didapat dari pertanyaan di atas, bagaimana peran G-20 dalam mengatasi krisis finansial global akibat free-trade tadi?
- Apakah fenomena intervensi G-20 dalam pasar, terutama sektor finansial menandakan berakhirnya era rezim laissez-faire ortodoks (monetarism policy) dalam mekanisme perekonomian global?
Dengan mengeksplorasi ketiga pertanyaan tersebut penulis bertujuan mencari tahu signifikansi peran negara dalam perekonomian global, khususnya terkait penanganan krisis finansial global pada kurun waktu 2007-2009.
2 Pertarungan ideologis dan sistem perekonomian dua adidaya (Perang Dingin) antara etatisme ala komunisme-sosialisme vis a vis pasar ekonomi terbuka (free trade) telah berakhir dengan kolapsnya Uni Soviet pada Desember 1991. AS bersama sekutunya masih bertahan hingga sekarang, sementara Uni-Soviet terpecah-pecah menjadi 17 negara.
3 Maksud Fukuyama adalah bahwa demokrasi liberal merupakan end point of mankind’s ideological evolution dan final form of human government sehingga proses sejarah manusia itu sendiri sudah mencapai puncaknya/tidak akan berubah lagi (baik menurut proses evolusi sejarah Hegel atau Marx).
4 Untuk penjelasan lebih mendalam mengenai Hegemonic Stability Theory, lih. contohnya Robert Gilpin, War and Change in World Politics, (New York: Oxford University Press, 16th edition 1999), terutama Bab V dan VI.
5 Wall Street Journal, "TED Spread spikes in July 2007", http://www.princeton.edu/~pkrugman/ted-spread-wsj.gif, diakses pada tanggal 29 Maret 2009.
6 AS adalah hegemon pengusung demokrasi liberal dan laissez-faire. Salah satu platform dasarnya adalah yang dikenal dengan nama “Washington Consensus”, lih. contohnya Ben Fine (ed.), Development Policy in the Twenty First Century: Beyond the Post Washington Consensus, (London: Routledge, 2001).
7 Menurut teori ekonomi klasik Adam Smith, harga pasar diciptakan keseimbangannya secara otomatis dan efisien karena digerakkan oleh dinamika persediaan (supply) dan permintaan/penawaran (demand) dalam pasar (market). Mekanisme dorongan keseimbangan tersebut disebut sebagai “the invisible hands”.
*Untuk membaca lebih lengkap atau ingin mengunduh tulisan ini silakan mengklik url link yang disediakan.
06 May 2009
Efektivitas Peran Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

oleh: Denis L. Toruan
-sinopasxinica- 7/5/09
Setujukah Anda bahwa peran Indonesia dalam Kerja sama Ekonomi ASEAN sudah efektif?
Pertama-tama, perlu diklarifikasi terlebih dahulu substansi dari pertanyaan ini. Setidaknya saya bisa menangkap dua interpretasi yang dapat dikemukakan darinya, yakni pertama, efektivitas bagi integrasi regional (ASEAN); dan kedua, efektivitas bagi pembangunan domestik Indonesia itu sendiri (RI’s national interest).[1] Tulisan singkat ini akan menjawab dengan mengacu dari dua interpretasi tersebut.
I. Efektivitas Peran Indonesia dalam Kerja sama Regional
Indonesia sejauh ini sudah berpartisipasi aktif dalam mendorong perumusan Bali Concord II Oktober 2003 maupun Cebu Declaration 13 Januari 2007 yang kemudian mendorong percepatan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi tahun 2015. Selain itu, Indonesia ikut meletakkan kerangka legal Piagam ASEAN (ASEAN Charter) pada 20 November 2007 sebagai basis komitmen. Politik luar negeri Indonesia pun juga jelas-jelas menyatakan bahwa ASEAN adalah batu penjuru bagi Indonesia sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak mendorong peningkatan kerja sama regional tersebut. Dalam dinamika regionalnya, Indonesia terbilang cukup konsisten dengan fokusnya tersebut, seperti yang terlihat dari dua indikator sebagai berikut:
- Indonesia memegang teguh the ASEAN Way
RI belum pernah secara eksplisit mencampuri urusan domestik negara-negara tetangganya (non-intervention). Indonesia bahkan melakukan inisiatif dalam menampung korban pengungsi Rohingya, contohnya, yang kita tahu merupakan pendatang ilegal karena krisis internal di Myanmar.[2]
- Indonesia juga memainkan polugri bebas aktif dan konsep balance of power dalam kerja sama regional
Indonesia tetap mendorong partisipasi terbatas dari dua negara besar seperti Amerika Serikat dan China dalam kerja sama regional. Ini dapat terlihat dari forum multilateral seperti ASEAN Regional Forum. Terkhusus mengenai kerja sama ekonomi, Indonesia juga mendorong kerja sama intrakawasan dengan negara-negara maju seperti ASEAN+3, dan juga inisiatif bilateral mutualisme seperti bilateral currency swap dengan China,[3] PTA dan FTA dengan Jepang, dll. Selain itu, mitra-mitra tradisional seperti Jepang, AS, Uni Eropa, dan China juga tetap menjadi partner dagang utama ASEAN yang secara bersama-sama memiliki pangsa pasar sekitar 44% dari total perdagangan ASEAN hingga tahun 2005.[4]
Dari segi normatif dan kesiapan mengantisipasi MEA 2015, Indonesia mulai mendorong berdirinya lembaga-lembaga independen/institusi nasional seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengawasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, sekaligus membantu peningkatan kualitas tenaga kerja secara regional.[5] Apabila pemerintah RI bisa fokus terhadap isu ini, asumsi terakhir tidak mungkin tidak menjadi teori dan kontribusi baru dalam peningkatan kerja sama ekonomi regional. Dalam bidang finansial dan investasi, Indonesia yang notabene tergabung dalam forum G-20 dan baru saja menyepakati komunike bersama tentang krisis finansial global, aktif dalam mendukung penanganan krisis secara multilateral, termasuk dalam penyediaan cadangan siaga IMF dan reformasi IMF itu sendiri (termasuk mendorong Chiang Mai Iniative/CMI bagi sektor finansial regionalnya). Sayangnya, hingga tulisan ini diturunkan, pengumuman ‘menggembirakan’ tersebut belum sempat dibahas dan ditindaklanjuti secara tuntas dalam forum ASEAN berhubung gagalnya KTT ASEAN di Phattaya, Thailand awal April lalu yang disebabkan oleh krisis internal Thailand.
Dengan berkaca pada indikator-indikator seperti di atas, hemat saya Indonesia sudah berperan efektif dalam integrasi regional ASEAN; RI konsisten dalam melakukan kebijakannya, meski sekali lagi perlu ditekankan bahwa hal tersebut kembali berpulang pada kesadaran dan political will RI untuk menyukseskan kerja sama ekonomi regional secara tuntas (even and complete) dan bertanggung jawab.
Sebagai negara anggota ASEAN dengan jumlah pasar potensial sebesar 220 juta jiwa (55% dari total populasi ASEAN) di kawasan bernilai ekonomi sebesar lebih dari 1,1 triliun dollar AS,[6] efektivitas peran Indonesia terhadap pembangunan domestiknya menjadi hal yang teramat penting untuk diabaikan begitu saja.
Kita semua tahu bahwa di atas kertas MEA 2015 akan membuka peluang bagi semakin bebasnya aliran modal, produk, jasa, hingga tenaga kerja ke seluruh kawasan ASEAN. Kesadaran itu sudah sepatutnya menjadi fokus RI dalam enam tahun yang tersisa sebelum konsep MEA 2015 itu benar-benar terealisasi. Implementasi konkretnya, RI masih harus memperbaiki playing field-nya, yakni seperti bagaimana meningkatkan kualitas/daya saing masyarakatnya, memperbaiki infrastruktur dan kerangka legal yang komprehensif, hingga meredifinisi politik luar negerinya. RI perlu membatasi dirinya pada kerja sama-kerja sama bilateral yang paling menguntungkan saja (terutama untuk jangka panjangnya), jangan sampai enam tahun yang tersisa malah terbuang sia-sia karena Indonesia belum sempat berbenah diri. Hal tersebut tidak berlebihan mengingat pamor dan kapabilitas (playing-field) negara besar seperti China mulai sedikit banyak ‘mendikte’ secara implisit orientasi ASEAN, sementara kekuatan pengimbang (balancing powers) seperti Jepang dan Korea Selatan mulai kedodoran, terutama setelah krisis finansial global menerjang.[7]
Proses pembenahan (management restructuring) ini masih terus berlangsung, dan membutuhkan perhatian serta kontribusi dari segenap aktor terkait, bukan hanya state actor itu sendiri. Salah satu indikator terbaik yang dapat saya kemukakan untuk menilai isu ini dapat dicermati dari neraca perdagangan RRI-RRC yang mulai timpang (harmful imbalance) hingga tahun 2008.[8] Indonesia harus benar-benar fokus terlebih dahulu terhadap kesiapan domestiknya. Dengan demikian, peran RI baru bisa efektif, terutama bagi segenap rakyat Indonesia yang menjadi konstituennya.
[1] ASEAN adalah “the cornerstone” (batu penjuru) bagi kebijakan luar negeri Indonesia, lih. www.deplu.go.id.
[2] Lih. beritanya di http://beritasore.com/2009/03/17/indonesia-perpanjang-masa-penampungan-pengungsi-rohingya/, diakses pada tanggal 5 Mei 2009.
[3] http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Berita/news_230309.htm, Gubernur Bank Indonesia, Dr. Boediono, dan Gubernur People’s Bank of China (PBC), DR. Zhou Xiaochuan, menandatangani perjanjian Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) pada Senin, 23 Maret 2009. Kerjasama Rupiah-Renmimbi swap line ini setara dengan Rp 175 triliun/RMB100 miliar, dan berlaku efektif selama 3 tahun dengan kemungkinan perpanjangan atas persetujuan keduabelah pihak.
[4] Sjamsul Arifin (ed.), Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 74–75.
[5] Asumsinya adalah menurunkan probabilitas mobilitas ekspor tenaga kerja RI yang cenderung unskilled-labour, belum semuanya legit, dan berpotensi menjadi masalah/beban di negara lain. Lih. penjelasannya di ibid., hlm. 278-280.
[6] Ibid., hlm. 12.
[7] Untuk penjelasan lebih mendalam tentang integrasi ekonomi kawasan Asia Timur dan perubahan-perubahan strukturnya, lih. contohnya Guillaume Gaulier (et.al.), China’s Integration in East Asia: Production Sharing, FDI and High-Tech Trade, (France: Springer Science+Business Media, 2007).
[8] Data dapat diakses di http://www.depdag.go.id/index.php?option=statistik&task=table&itemid=06010202.