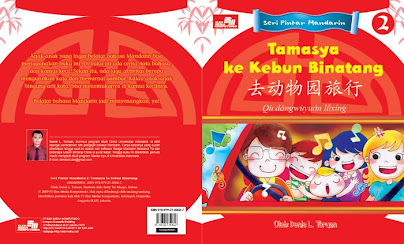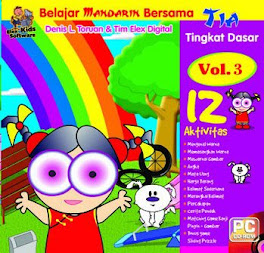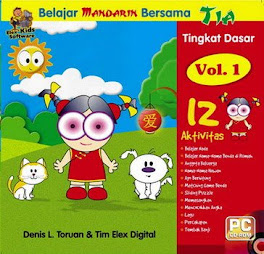oleh: Denis L. Toruan
-sinopasxinica- 7/5/09
Setujukah Anda bahwa peran Indonesia dalam Kerja sama Ekonomi ASEAN sudah efektif?
Pertama-tama, perlu diklarifikasi terlebih dahulu substansi dari pertanyaan ini. Setidaknya saya bisa menangkap dua interpretasi yang dapat dikemukakan darinya, yakni pertama, efektivitas bagi integrasi regional (ASEAN); dan kedua, efektivitas bagi pembangunan domestik Indonesia itu sendiri (RI’s national interest).[1] Tulisan singkat ini akan menjawab dengan mengacu dari dua interpretasi tersebut.
I. Efektivitas Peran Indonesia dalam Kerja sama Regional
Indonesia sejauh ini sudah berpartisipasi aktif dalam mendorong perumusan Bali Concord II Oktober 2003 maupun Cebu Declaration 13 Januari 2007 yang kemudian mendorong percepatan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi tahun 2015. Selain itu, Indonesia ikut meletakkan kerangka legal Piagam ASEAN (ASEAN Charter) pada 20 November 2007 sebagai basis komitmen. Politik luar negeri Indonesia pun juga jelas-jelas menyatakan bahwa ASEAN adalah batu penjuru bagi Indonesia sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak mendorong peningkatan kerja sama regional tersebut. Dalam dinamika regionalnya, Indonesia terbilang cukup konsisten dengan fokusnya tersebut, seperti yang terlihat dari dua indikator sebagai berikut:
- Indonesia memegang teguh the ASEAN Way
RI belum pernah secara eksplisit mencampuri urusan domestik negara-negara tetangganya (non-intervention). Indonesia bahkan melakukan inisiatif dalam menampung korban pengungsi Rohingya, contohnya, yang kita tahu merupakan pendatang ilegal karena krisis internal di Myanmar.[2]
- Indonesia juga memainkan polugri bebas aktif dan konsep balance of power dalam kerja sama regional
Indonesia tetap mendorong partisipasi terbatas dari dua negara besar seperti Amerika Serikat dan China dalam kerja sama regional. Ini dapat terlihat dari forum multilateral seperti ASEAN Regional Forum. Terkhusus mengenai kerja sama ekonomi, Indonesia juga mendorong kerja sama intrakawasan dengan negara-negara maju seperti ASEAN+3, dan juga inisiatif bilateral mutualisme seperti bilateral currency swap dengan China,[3] PTA dan FTA dengan Jepang, dll. Selain itu, mitra-mitra tradisional seperti Jepang, AS, Uni Eropa, dan China juga tetap menjadi partner dagang utama ASEAN yang secara bersama-sama memiliki pangsa pasar sekitar 44% dari total perdagangan ASEAN hingga tahun 2005.[4]
Dari segi normatif dan kesiapan mengantisipasi MEA 2015, Indonesia mulai mendorong berdirinya lembaga-lembaga independen/institusi nasional seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengawasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, sekaligus membantu peningkatan kualitas tenaga kerja secara regional.[5] Apabila pemerintah RI bisa fokus terhadap isu ini, asumsi terakhir tidak mungkin tidak menjadi teori dan kontribusi baru dalam peningkatan kerja sama ekonomi regional. Dalam bidang finansial dan investasi, Indonesia yang notabene tergabung dalam forum G-20 dan baru saja menyepakati komunike bersama tentang krisis finansial global, aktif dalam mendukung penanganan krisis secara multilateral, termasuk dalam penyediaan cadangan siaga IMF dan reformasi IMF itu sendiri (termasuk mendorong Chiang Mai Iniative/CMI bagi sektor finansial regionalnya). Sayangnya, hingga tulisan ini diturunkan, pengumuman ‘menggembirakan’ tersebut belum sempat dibahas dan ditindaklanjuti secara tuntas dalam forum ASEAN berhubung gagalnya KTT ASEAN di Phattaya, Thailand awal April lalu yang disebabkan oleh krisis internal Thailand.
Dengan berkaca pada indikator-indikator seperti di atas, hemat saya Indonesia sudah berperan efektif dalam integrasi regional ASEAN; RI konsisten dalam melakukan kebijakannya, meski sekali lagi perlu ditekankan bahwa hal tersebut kembali berpulang pada kesadaran dan political will RI untuk menyukseskan kerja sama ekonomi regional secara tuntas (even and complete) dan bertanggung jawab.
Sebagai negara anggota ASEAN dengan jumlah pasar potensial sebesar 220 juta jiwa (55% dari total populasi ASEAN) di kawasan bernilai ekonomi sebesar lebih dari 1,1 triliun dollar AS,[6] efektivitas peran Indonesia terhadap pembangunan domestiknya menjadi hal yang teramat penting untuk diabaikan begitu saja.
Kita semua tahu bahwa di atas kertas MEA 2015 akan membuka peluang bagi semakin bebasnya aliran modal, produk, jasa, hingga tenaga kerja ke seluruh kawasan ASEAN. Kesadaran itu sudah sepatutnya menjadi fokus RI dalam enam tahun yang tersisa sebelum konsep MEA 2015 itu benar-benar terealisasi. Implementasi konkretnya, RI masih harus memperbaiki playing field-nya, yakni seperti bagaimana meningkatkan kualitas/daya saing masyarakatnya, memperbaiki infrastruktur dan kerangka legal yang komprehensif, hingga meredifinisi politik luar negerinya. RI perlu membatasi dirinya pada kerja sama-kerja sama bilateral yang paling menguntungkan saja (terutama untuk jangka panjangnya), jangan sampai enam tahun yang tersisa malah terbuang sia-sia karena Indonesia belum sempat berbenah diri. Hal tersebut tidak berlebihan mengingat pamor dan kapabilitas (playing-field) negara besar seperti China mulai sedikit banyak ‘mendikte’ secara implisit orientasi ASEAN, sementara kekuatan pengimbang (balancing powers) seperti Jepang dan Korea Selatan mulai kedodoran, terutama setelah krisis finansial global menerjang.[7]
Proses pembenahan (management restructuring) ini masih terus berlangsung, dan membutuhkan perhatian serta kontribusi dari segenap aktor terkait, bukan hanya state actor itu sendiri. Salah satu indikator terbaik yang dapat saya kemukakan untuk menilai isu ini dapat dicermati dari neraca perdagangan RRI-RRC yang mulai timpang (harmful imbalance) hingga tahun 2008.[8] Indonesia harus benar-benar fokus terlebih dahulu terhadap kesiapan domestiknya. Dengan demikian, peran RI baru bisa efektif, terutama bagi segenap rakyat Indonesia yang menjadi konstituennya.
[1] ASEAN adalah “the cornerstone” (batu penjuru) bagi kebijakan luar negeri Indonesia, lih. www.deplu.go.id.
[2] Lih. beritanya di http://beritasore.com/2009/03/17/indonesia-perpanjang-masa-penampungan-pengungsi-rohingya/, diakses pada tanggal 5 Mei 2009.
[3] http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Berita/news_230309.htm, Gubernur Bank Indonesia, Dr. Boediono, dan Gubernur People’s Bank of China (PBC), DR. Zhou Xiaochuan, menandatangani perjanjian Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) pada Senin, 23 Maret 2009. Kerjasama Rupiah-Renmimbi swap line ini setara dengan Rp 175 triliun/RMB100 miliar, dan berlaku efektif selama 3 tahun dengan kemungkinan perpanjangan atas persetujuan keduabelah pihak.
[4] Sjamsul Arifin (ed.), Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 74–75.
[5] Asumsinya adalah menurunkan probabilitas mobilitas ekspor tenaga kerja RI yang cenderung unskilled-labour, belum semuanya legit, dan berpotensi menjadi masalah/beban di negara lain. Lih. penjelasannya di ibid., hlm. 278-280.
[6] Ibid., hlm. 12.
[7] Untuk penjelasan lebih mendalam tentang integrasi ekonomi kawasan Asia Timur dan perubahan-perubahan strukturnya, lih. contohnya Guillaume Gaulier (et.al.), China’s Integration in East Asia: Production Sharing, FDI and High-Tech Trade, (France: Springer Science+Business Media, 2007).
[8] Data dapat diakses di http://www.depdag.go.id/index.php?option=statistik&task=table&itemid=06010202.